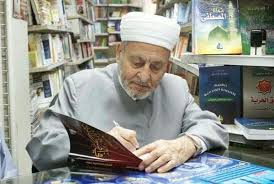Peran Perempuan dalam Pendidikan
Islam memberikan ruang dan dimensi bagi perempuan untuk berperan bagi bangsa dan agamanya. Peran itu berupa pengangkatan harkat dan derajat perempuan di ruang publik, di mana eksistensi mereka tidak lagi dikekang baik oleh lembaga yang terkecil seperti keluarga, maupun dalam wilayah yang lebih luas.
Posisi perempuan dalam kehidupan sebagaimana disebutkan dalam al-Quran, pada dasarnya, setara dengan laki-laki. Hal ini disimbolkan dengan ungkapan diciptakan “berpasangan” yang mengandung makna implisit akan kesetaraan dalam ruang sosial.
Perempuan, setelah diangkat martabatnya memiliki hak dan peran besar untuk mengembangkan masyarakat. Hal itu bisa kita tilik pada sejarah awal perkembangan peradaban Islam. Istri Nabi, Guru para generasi Tabi’in (kibar al-tabi’iin), Aisyah Ra merupakan gambaran atau contoh diakuinya eksistensi dan peran perempuan dalam masyarakat.
Pada generasi Islam ke-2, sejarah menampilkan aksi-aksi kaum perempuan di ranah publik. sebut saja, Rabi’ah al-‘Adawiyah (Guru Sufi), Sayyidah Nafisah (sahabat sekaligus guru Imam al-Syafi’i).
Peran perempuan dalam pendidikan pun menentukan peradaban suatu bangsa dan agama. Lewat pengajaran ilmu-ilmu agama umat bisa memahami, meyakini, dan mengamalkannya. Di antara banyaknya cendekiawan tentu ada segilintir kaum perempuan yang ikut dalam mengembangkan dan mencerdaskan umat dan bangsa. Adanya pengakuan posisi dan peran perempuan baik oleh nash-nash Islam, ataupun dalam sejarah, mendorong para founding father bangsa untuk menerjemahkan peran tersebut dalam UUD 1945 dengan tujuan “mencerdaskan kehidupan bangsa”.
Dalam tradisi Arab Jahiliyyah, perempuan masih di[individualisasi]kan, dimarginalkan, serta dipersempit ruang gerak dan perannya. Ini terjewantahkan dalam ungkapan :
نَصْرُهَا بُكَاءٌ وَبِرُّهَا سَرِقَةٌ
Pembelaan perempuan ialah tangisan dan baktinya adalah mencuri.
Dengan demikian dalam urusan domestik saja, perempuan – pada masa jahiliah- bisa dikatakan tidak dianggap, apalagi memberikan apresiasi, ruang gerak untuk berkontribusi dalam lingkup sosial.
Pendidikan berawal dari lingkup yang paling kecil yaitu keluarga. Nah, dari sini kemudian perempuan bisa mengembangkan pendidikannya dengan menempuh jalur pendidikan formal atau nonformal, di satu sisi. Di sisi lain, langkah ini bergandengan dengan peran pengajaran yang bisa ditransfer kepada masyarakat.
Melalui pengajaran inilah keberadaan perempuan terangkat secara alami dengan munculnya kesadaran kaum laki-laki untuk menyejajarkan posisi yang tidak lagi berelasi dengan alat vital -sebagaimana dalam gagasan Freudian-, tapi kesadaran (counciousness) yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari al-Quran dan Hadis Nabi.
Rasanya tidak mungkin untuk menjelaskan peran perempuan dalam berbagai sisi kehidupan. Terkadang, kita hanya cukup memahami realita yang hadir di hadapan kita untuk menerjemahkan ulang tentang perempuan. Dalam berbagai permasalahan pendidikan, tidak dapat dipungkiri betapa dibutuhkannya kontribusi perempuan. Sebut saja, pendidikan tentang fikih perempuan. Pada kondisi ini, pengajar yang paling tepat tentulah perempuan.
Dalam konteks sejarah pergerakan nasional, nama Dewi Sartika tidak lebih dikenal dibandingkan Kartini karena nama ini (di)absen(kan) dalam sejarah “resmi”. Lewat Pramoedya-lah Dewi Sartika ditampilkan-balik sebagai pejuang bagi kalangan perempuan di ranah publik, khususnya pendidikan. Nama lain yang tak asing, Nyai Hj. Siti Walidah, Istri KH. Ahmad Dahlan, juga menjadi contoh tepat untuk menunjukkan pergerakan kaum perempuan di bidang pendidikan.
Pendidikan ini meningkatkan nasionalisme rakyat sesuai dengan pernyataan kemerdekaaan “ialah hak segala bangsa”. Pendeknya, bahwa perempuan mampu berjuang untuk mendapatkan hak-haknya. Di antara hak-hak itu ialah mendapatkan pengajaran dan mentransferkan ilmu dan pengetahuan dalam rangka “mencerdaskan kehidupan bangsa”.
Dari contoh di atas, dapat kita lihat bagaimana sejarah pergerakan nasional menghargai keberadaan kaum hawa dan memberikan peran yang besar bagi mereka untuk berjuang. Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan Aisyah Ra, Rasulullah Saw bersabda;
إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ
“Bahwasanya perempuan itu merupakan saudara kandung laki-laki” (HR. Bukhari, al-Tirmidzi, Ibnu Majah)
Hadis ini berbicara tentang mandi besar. Di dalamnya terdapat perumpamaan Nabi Saw yang menunjukkan persamaan antara kaum perempuan dengan laki-laki. Badr al-Din al-A’ini dalam ‘Umdat al-Qâri’ syarah Shahih al-Bukhari memaknai Hadis di atas bahwa perempuan serupa dan sama dengan kaum laki-laki dalam akhlak dan etikanya.”
Ulama-ulama menyetujui bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum, kecuali ada nash yang menjelaskannya.
Penghargaan akan kesetaraan perempuan dan peran mereka melawan kebodohan umat tidak diragukan lagi. Prinsip ini telah diakui bersama berdasarkan sumber teks-teks transenden, sebagaimana firman Allah:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.” (QS. al-Hujurat: 13)
Imam Ibnu Katsir menafsiri ayat di atas bahwa semua orang dipandang sama secara kemanusiaan (basyariah). Perbedaan terletak pada sisi agama (diniyah) lewat ketaatan, mengikuti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad serta berbuat kebajikan.
Keberadaan wanita merupakan syarat mutlak untuk melanjutkan peradaban manusia. Dari adam dan hawa tonggak keberadaan manusia bermula. Hubungan biologis melahirkan manusia baru, hubungan laki-laki dan perempuan tidak lagi sebatas hasrat dan kesenangan, tetapi lebih kepada hubungan fitrah yang memastikan tetap berjalannya roda peradaban.
Peradaban lahir dari interaksi (ta’aaruf) antara satu bangsa dengan bangsa lain melalui pikir, tradisi, budaya atau kesetaran dalam mendapatkan pengetahuan. Pada titik inilah Islam telah terjewantahkan sebagai rahmatan lil ‘alamin bukan sebagai master signifer tapi sebagai perwujudan dari etika sosial.
Perbedaan tidak ditentukan oleh status, posisi, apalagi oleh kekuatan, tetapi diterjemahkan lewat kemuliaan dan keutamaan yang teraplikasikan melalui kebaikan. Perantara (washilah) yang baik sama nilainya dengan tujuan (maqshad). Harus diakui, bahwa lewat pemberian sarana itulah kita bisa memberikan ruang gerak yang luas untuk kaum perempuan, terutama dalam bidang pendidikan.
Pemberian sarana bagi perjuangan perempuan tentu akan berbuah ganjaran yang serupa dengan tujuan perjuangan yang ingin dicapai.
Pemuliaan dan pengangkatan harkat perempuan dalam konteks sosial telah diwujudkan dalam sejarah Islam. Pemuliaan tentunya berbanding lurus dengan pemberian hak-hak, dan peran yang signifikan karena keduanya merupakan dua hal yang saling terikat.
Ketentuan-ketentuan Allah itu bersifat qath’i atau apa yang disebut oleh ahli hukum Islam dengan tsawaabit (hal-hal yang tetap/ konstan). Keadilan dan kesetaraan merupakan contoh tsawaabit. Ada juga hal-hal yang berubah (mutaghayyarat) yang direferensikan kepada peran. Tentu peran itu bisa jadi berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan konteks sebuah perjuangan.
Hukum Islam pada intinya menggaungkan keadilan dan membebaskan manusia dari penindasan. Pada sisi lain, pengembangan intelegensi perempuan merupakan syarat tersendiri bagi mereka agar bisa menyuarakan hak-haknya. Karena pada dasarnya perempuanlah yang bisa berbicara, mempresentasikan keperempuanannya. Pemberian peran memiliki signifikansi kepada perempuan yang mampu menghilangkan jurang perbedaan peran di kehidupan masyarakat.
Wallahu a’lam.***