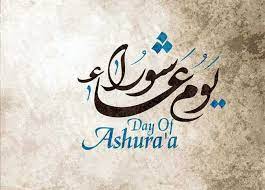Wahabi dan NU dalam Pandangan Kiai Ali Mustafa Yaqub
Persatuan dan kesatuan umat Islam adalah impian setiap muslim. Meskipun sudah diperjuangkan dengan sangat maksimal, perbedaan memang tidak dapat dihindari dan dihilangkan. Dengan demikian, perbedaan dan keragaman bukanlah masalah, namun jika tidak dikelola dengan baik, justru akan menjadi sumber masalah. Tidak siap menerima perbedaan dan cenderung membesar-besarkannya, apalagi hanya menyangkut hal yang tidak prinsip, adalah sikap yang harus dihindari. Hal yang paling miris dari ekses perbedaan yang tidak dikelola dengan baik adalah tumbuhnya rasa nyaman dan nikmat dalam perpecahan dan permusuhan, hanya karena kepentingan sejenak dari beberapa pihak.
Perbedaan dapat berubah menjadi perpecahan manakala ditunggangi oleh kepentingan dan tidak dilakukan dialog yang baik. Dalam konteks Indonesia, Islam yang melembaga dalam banyak ormas juga sangat rawan mengarah kepada perpecahan. Budaya “katanya” yang menjangkiti umat Islam di Indonesia turut berkontribusi dalam melahirkan perpecahan karena membawa informasi yang seringkali bias. Budaya klarifikasi dan membangun persatuan dalam keberagaman tampaknya hanya akan menjadi cita-cita yang utopis selama budaya “katanya” masih dibiarkan mewabah. Sikap paling bijak dalam hal ini adalah membasmi budaya “katanya” tanpa harus menghilangkan perbedaan atau keragaman ormas. Hal lain yang harus dikedepankan bukanlah sikap mencari-cari siapa yang salah dan siapa yang benar.
Umat Islam Indonesia seringkali diributkan oleh masalah perbedaan pemikiran keagamaan yang tidak jarang berujung pada permusuhan. Syiah, Ahmadiyah, Salafi-Wahabi adalah beberapa contoh gerakan pemikiran keagamaan yang seringkali terdengar keterlibatannya dalam konflik sosial. Hingga kini, telah banyak penulis yang menyerukan secara tegas untuk berdamai dengan Syiah, Ahmadiyah, atau dengan agama apapun di dunia ini. Namun, tampak sangat sedikit sekali—atau bahkan belum ada—seruan perdamaian antara NU dan Wahhabi.